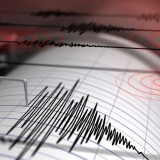TIMES MALUKU, MALUKU – Indonesia memiliki sejarah kelam yang tidak bisa dihapus dari ingatan kolektif bangsa, yakni krisis multidimensi pada tahun 1998. Kala itu, negeri ini diguncang krisis ekonomi dan moneter yang disulut oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Beban utang luar negeri yang jatuh tempo, inflasi yang tak terkendali, hingga anjloknya nilai rupiah terhadap dolar Amerika. Krisis itu diperparah dengan hilangnya kepercayaan publik terhadap kepemimpinan nasional, sehingga menciptakan gejolak sosial besar yang mengubah wajah bangsa.
Fenomena demonstrasi yang marak terjadi di berbagai daerah saat ini sejatinya merupakan gema dari peristiwa serupa. Amarah massa bukan muncul tiba-tiba, melainkan lahir dari akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang semakin sulit.
Daya tahan warga kecil kian rapuh, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar saja, mereka merasa makin kesulitan. Dalam bahasa sederhana, isi perut masyarakat kelas bawah mulai sulit diisi.
Gelombang protes tersebut memperlihatkan bahwa persoalan bangsa tidak hanya bersumber pada faktor ekonomi, tetapi juga karena lemahnya kepercayaan publik terhadap kebijakan negara.
Selama ini, banyak kebijakan yang dianggap prematur, tidak berpihak pada rakyat, dan gagal menjawab keresahan sosial. Kekecewaan publik kian menguat ketika menyaksikan berbagai keputusan politik dan ekonomi yang justru memperlebar jarak antara elite dan masyarakat.
Mulai dari polemik kenaikan pajak yang memantik kegelisahan, kebijakan anggaran pendidikan yang dirasa tidak berpihak pada generasi muda, lemahnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus besar korupsi, hingga kontroversi seputar kenaikan hak keuangan anggota DPR RI yang kontras dengan kondisi rakyat yang semakin terhimpit.
Rakyat juga menyaksikan fenomena birokrasi yang gemuk dengan banyaknya jabatan wakil menteri, praktik rangkap jabatan pejabat sebagai komisaris, serta munculnya berbagai pernyataan pejabat publik yang terkesan merendahkan akal sehat rakyat.
Tidak berhenti di situ, isu perburuhan terkait upah, outsourcing, hingga dampak UU Cipta Kerja semakin menambah daftar panjang keresahan publik. Semua ini membentuk satu kesadaran kolektif: negara tampak lebih sibuk mengurus kepentingan elite daripada memikirkan kesejahteraan masyarakat luas.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa yang sedang dihadapi bangsa ini bukan sekadar krisis ekonomi, melainkan krisis kepercayaan. Distrust yang lahir dari masyarakat mencerminkan runtuhnya legitimasi kebijakan di mata publik.
Jika hal ini tidak segera ditangani, bangsa ini berpotensi terjerumus pada krisis legitimasi seperti yang terjadi pada 1998, meski dengan wajah dan konteks yang berbeda.
Untuk menghindari itu, langkah strategis yang perlu ditempuh pemerintah adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Negara harus berani mengambil jeda, meninjau ulang arah kebijakan, lalu melahirkan keputusan yang lebih populis, adil, dan berpihak pada rakyat kecil.
Kebijakan publik tidak boleh sekadar menjadi alat kapitalisasi yang menguntungkan segelintir pihak, melainkan harus kembali pada spirit Pancasila, yakni menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Di sisi lain, DPR RI sebagai wakil rakyat harus membuktikan dirinya benar-benar layak disebut “rumah aspirasi.” Tuntutan masyarakat yang disampaikan lewat demonstrasi seharusnya tidak dianggap ancaman, melainkan sinyal bahwa rakyat masih peduli dan ingin didengar.
Upaya sebagian anggota DPR untuk menghindar, bahkan mencari perlindungan ke luar negeri, jelas bukan solusi cerdas, melainkan justru memperlebar jurang ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif.
Demonstrasi hari ini adalah alarm keras bagi negara. Ia bukan sekadar ekspresi kemarahan spontan, tetapi cerminan dari krisis kepercayaan ekonomi dan politik yang semakin dalam. Jika pemerintah dan DPR memilih untuk menutup mata, sejarah kelam 1998 bisa saja berulang dengan pola berbeda.
Jalan terbaik bukanlah menekan suara rakyat, melainkan merangkulnya dengan kebijakan yang adil, solutif, dan berpihak kepada kepentingan publik. Sebab, pada akhirnya legitimasi sebuah negara hanya akan kokoh bila berdiri di atas fondasi kepercayaan rakyatnya.
***
*) Oleh : Prof. Dr. Sofyan Abas, Dosen Ekonomi dan Keuangan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
Artikel ini sebelumnya sudah tayang di TIMES Indonesia dengan judul: Demonstrasi Publik dan Distrust Ekonomi Indonesia
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |