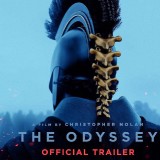TIMES MALUKU, MALUKU – Kejahatan terhadap kemanusiaan tidak lahir dari kebengisan semata, tetapi dari ketidakmampuan manusia berpikir secara kritis dan reflektif. Dalam sejarah, kekerasan sering dimulai dari pembenaran yang lahir dari keacuhan moral. Pelaku menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang wajar, bahkan sah, selama dilakukan atas nama kekuasaan, ideologi, atau perintah atasan.
Di sinilah, sebagaimana diungkap oleh Hannah Arendt, lahir konsep yang mengguncang dunia filsafat politik: banality of evil banalitas kejahatan. Kejahatan yang dilakukan bukan karena kebencian mendalam, melainkan karena rutinitas tanpa pikiran.
Dalam banyak kasus, kejahatan terhadap kemanusiaan justru dilakukan oleh negara, lewat kebijakan yang menindas dan mematikan nalar publik. Namun, ia juga bisa muncul dari kelompok bersenjata non-negara, paramiliter, atau milisi yang kehilangan kepekaan etis dan menjadikan kekuasaan sebagai satu-satunya hukum.
Dari sinilah kita memahami bahwa kekerasan bukan hanya tindakan fisik, tetapi juga gejala dari krisis kemanusiaan yang mendalam krisis berpikir, krisis nilai, dan krisis nurani.
Secara teologis, kejahatan selalu menjadi misteri. Ia menghadirkan paradoks antara keyakinan akan kebaikan Tuhan dan realitas penderitaan manusia. Dalam tradisi Hindu Vedanta, sebagaimana dijelaskan dalam ajaran monisme, kejahatan dipandang sebagai maya, ilusi.
Mary Baker Eddy, tokoh spiritual Kristen Barat, juga menyebut kejahatan sebagai ilusi dalam karyanya Science and Health, bahwa ia tak memiliki wujud sejati kecuali yang diberikan manusia sendiri. Namun dalam pengalaman manusia, kejahatan terasa nyata, menimbulkan luka, kemiskinan, dan penderitaan.
Ada kejahatan yang bersifat alami banjir, gempa, wabah yang bersifat nisbi. Tapi kejahatan yang paling berbahaya adalah kejahatan yang lahir dari kehendak manusia sendiri, ketika akal sehat dan empati dilumpuhkan oleh ambisi dan ketakutan.
Kekerasan dapat berwujud dalam banyak bentuk: penindasan politik, eksploitasi ekonomi, korupsi, hingga perdagangan manusia. Semua itu bermuara pada satu hal: perampasan martabat manusia.
Kejahatan kemanusiaan bukan hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga luka psikologis yang panjang. Trauma akibat kekerasan, teror, atau perang tidak berhenti pada individu, tapi menular ke keluarga, masyarakat, bahkan generasi berikutnya.
Abdurrahman dan Abu Rayyan membedakan bentuk teror menjadi dua: teror fisik, yang melukai tubuh dan menimbulkan rasa takut nyata; dan teror mental, yang menekan jiwa hingga korban kehilangan harapan, putus asa, bahkan memilih mati. Dalam konteks ini, teror adalah cara paling efektif untuk membunuh kemanusiaan tanpa peluru.
Kita melihat bagaimana banalitas kejahatan itu menjelma nyata di Sudan. Konflik yang berkepanjangan antara militer dan kelompok paramiliter bukan hanya perang kekuasaan, tetapi juga perang melawan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.
Dalam sistem yang meniadakan tanggung jawab individu, orang-orang “normal” menjadi pelaku kekerasan luar biasa. Mereka tidak bertanya lagi tentang moralitas, hanya menjalankan perintah. Tragedi Darfur menunjukkan hal itu: sejarah panjang ketimpangan sosial, krisis sumber daya alam, dan kegagalan pemerintahan sipil telah melahirkan siklus kekerasan yang tak berujung.
Sudan menjadi cermin bagaimana negara gagal menjadi pelindung, dan justru menjadi mesin kekerasan. Lebih dari lima belas kali kudeta militer terjadi sejak kemerdekaan tahun 1956.
Sejak konflik meletus pada 2023, lebih dari 14 juta orang mengungsi, dan 140 ribu nyawa melayang. Negara yang kaya minyak dan emas itu kini menjadi kuburan kemanusiaan. Di balik angka-angka itu, ada air mata, rasa takut, dan kehilangan harapan.
Krisis serupa juga menjalar di Timur Tengah. Konflik berkepanjangan di Palestina, Suriah, Yaman, dan Lebanon telah menelanjangi wajah dunia modern: sebuah peradaban yang canggih secara teknologi, tapi gagal secara moral.
Pembunuhan massal, kelaparan, dan kehancuran infrastruktur menjadi bukti bahwa kekuasaan lebih dihargai daripada kehidupan manusia. Kekerasan kini menjadi bahasa politik yang paling universal.
Hannah Arendt menegaskan, kekerasan memang sering dipakai untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, tetapi ketika ia dijadikan tujuan, kekuasaan justru kehilangan maknanya. Kekerasan, kata Arendt, hanya rasional selama ia menjadi alat untuk membangun keadilan. Ketika kekerasan berdiri sendiri, ia berubah menjadi kehancuran total tidak hanya menghancurkan yang dikuasai, tapi juga yang menguasai.
Pemikiran Lenin tentang abad ke-19 sebagai abad peperangan terbukti di abad ke-20: dua perang dunia, genosida, dan revolusi. Tapi Arendt menambahkan, kekerasan bukan bagian dari kekuasaan ia adalah kegagalan kekuasaan.
Negara yang terlalu bergantung pada kekerasan menunjukkan lemahnya legitimasi moralnya. Inilah sebabnya kekerasan sering digunakan oleh rezim otoriter yang kehilangan kepercayaan publik, yang menindas rakyat atas nama stabilitas, dan menebar ketakutan atas nama ketertiban.
Ali Syari’ati kemudian memberi perspektif spiritual terhadap hal ini. Ia mengkritik humanisme Barat dan Marxisme yang memandang manusia hanya dari sisi material. Menurutnya, manusia bukan sekadar tubuh, tetapi makhluk spiritual dengan martabat tinggi.
Dalam pandangan Syari’ati, sejarah manusia adalah dialektika antara dua kutub: Habil dan Qabil antara kaum tertindas yang mencari keadilan, dan kaum penindas yang mempertahankan kekuasaan. Sejarah bukanlah kebetulan, tetapi medan abadi pertarungan antara kebenaran dan kebatilan.
Dari sanalah kita belajar bahwa kejahatan kemanusiaan selalu lahir dari struktur sosial yang timpang ketika manusia dipaksa tunduk pada sistem yang meniadakan nalar kritis. Ketika kepatuhan lebih dihargai daripada keberanian berpikir, maka kekerasan akan terus berulang dalam bentuk yang baru. Kejahatan tidak selalu datang dari mereka yang beringas; sering kali justru dilakukan oleh mereka yang diam, patuh, dan berhenti berpikir.
Hannah Arendt pernah menulis, “Kejahatan terbesar di dunia ini dilakukan bukan oleh monster, tetapi oleh orang-orang biasa yang menolak berpikir.” Maka, melawan kejahatan bukan sekadar tugas moral, melainkan tugas intelektual dan spiritual.
Ia menuntut keberanian untuk berpikir, bertanya, dan menolak tunduk pada sistem yang menindas nurani. Karena hanya dengan berpikir kritis dan berempati, manusia dapat kembali menemukan hakikatnya sebagai makhluk berakal, bebas, dan bermartabat.
***
*) Oleh : Sahib Munawar, S.Pd,I., M.,Pd., Akademisi, Pegiat Filsafat dan literasi Maluku Utara.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |